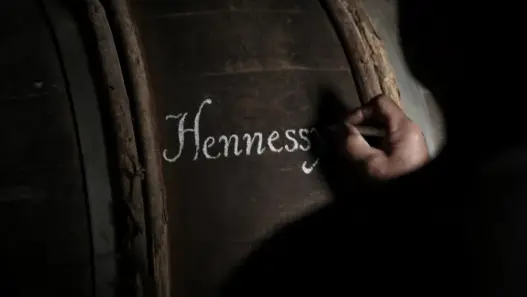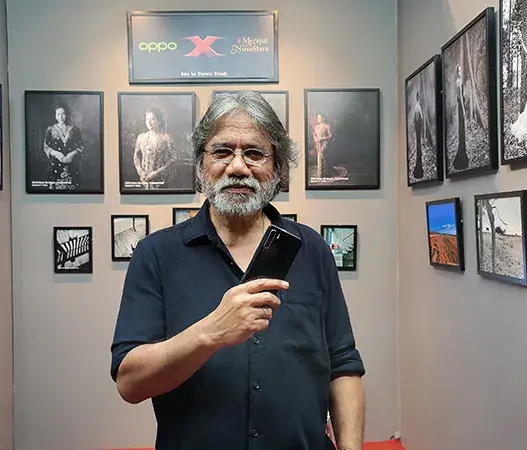Ada kebingungan tentang apa yang benar-benar membuat kita bahagia. Banyak orang berpikir bahwa harta benda memuaskan hasrat dan membawa kesenangan. Yang terlihat kasat mata, uang dapat membeli kebahagiaan. Kelilingi saja diri Anda dengan barang-barang berkualitas prima, niscaya kebahagiaan akan datang. Namun jauh di lubuk hati, kita tidak benar-benar menginginkan lebih banyak barang. Yang kita inginkan adalah merasa utuh.
Tentunya jangan lantas menanggapi pernyataan di atas dengan meninggalkan setengah barang-barang yang Anda miliki di rumah. Para minimalis memulai proses dengan decluttering atau merapikan rumah. Proses decluttering ini menyeleksi mana benda yang punya nilai guna dan tidak. Benda tidak terpakai akan disingkirkan. Bertanyalah pada diri Anda sendiri, mengapa punya benda ini? Apa fungsinya? Apa kita sangat membutuhkannya? Apa jadinya jika tetap disimpan? Bagaimana hidup kita kalau disingkirkan? Apa orang lain lebih membutuhkan?
Pertanyaan tersebut juga muncul saat ingin melakukan pembelian benda. Mereka menekan hasrat memiliki dan memilih sesuai kebutuhan agar tidak terjadi penimbunan. Dalam film dokumenter Minimalism: A Documentary About the Important Things karya Matt D'Avella, seorang psikolog Dr. Randy O. Frost menyatakan dengan menimbun barang, kita tidak hanya memiliki barang-benda di rumah. Tetapi mereka juga memiliki kita. Objek membawa beban tanggung jawab yang mencakup perolehan, penggunaan, perawatan, penyimpanan, dan pembuangan. Harta memiliki energi magis, esensi yang melampaui karakteristik fisik mereka. Benda tidak perlu diberi arti lagi karena ia sudah memiliki makna dan fungsinya sendiri. Semua bisa diganti jika sudah tidak berfungsi sama sekali. Cara ini memudahkan proses decluttering karena tidak adanya hubungan emosional terhadap benda.
Proses decluttering menghasilkan perasaan lega, keleluasaan ruang, fokus, dan produktifitas optimal. Dalam situs Psychology Today, Psikolog lingkungan dan desain Sally Augustin, Ph.D. berpendapat orang-orang akan berada dalam suasana hati lebih baik saat berada di tempat-tempat yang lebih teratur daripada tidak terorganisir. Secara mental, menurutnya, melelahkan bagi kita untuk melihat kekacauan dari tumpukan benda. Ruang beserta benda yang menyertainya memberikan gambaran tentang siapa kita.Terlalu banyak benda menyiratkan kurangnya kendali dan mengaburkan indentitas kita sendiri.

Perubahan besar tidak didapatkan dari berbenah ruang saja. Decluttering juga diterapkan terhadap pikiran. Seperti ruang tak berbatas, apapun bisa ada di dalam kepala kita, dari yang menguntungkan sampai gangguan. “Kita bisa mengumpulkan gangguan seperti tugas harian, acara, atau hubungan dan menyingkirkannya tanpa penyesalan. Dengan melakukan itu, kita bebas untuk memfokuskan perhatian berupa waktu, energi, dan uang kita pada hal-hal yang benar-benar membuat kita bahagia,” ungkap Sarah Knight penganut minimalisme di TED Talks. Ia memperkenalkan konsep untuk tidak memberikan perhatian untuk segala hal yang sebenarnya kurang penting tanpa merasa bersalah. “Jadi, jika Anda tidak peduli tentang sesuatu, Anda harus berhenti memberikan perhatian padanya. Saya tidak peduli tentang Game of Thrones jadi saya tidak menghabiskan waktu menontonnya, saya enggan membuang energi mempertanyakan bagaimana kisah musim berikutnya, dan saya tidak menghabiskan uang saya untuk buku, atau barang dagangan, atau apa pun. Game of Thrones tidak mendapatkan perhatian saya,” ia menambahkan.
Demikian pula hubungan kurang berkualitas dalam kehidupan masyarakat yang acap kali terpaksa dijalin atas nama menjaga hubungan baik. “Anda mungkin harus bangun dan pergi bekerja setiap hari dan menghadiri beberapa pertemuan wajib. Tetapi Anda tidak harus menghadiri pesta dan bertemu orang yang tidak Anda sukai. Anda membuang-buang waktu, energi, dan uang untuk itu karena merasa wajib dan bersalah,” kata Sarah lagi. Orang minimalis menyortir lingkarannya sendiri. Dipastikan, orang-orang yang berada di dalam setiap hubungannya merupakan yang terbaik.
Urusan merapikan kehidupan tidak berhenti sampai di situ. Ponsel dan media sosial turut ada di dalamnya. Minimalisme digital perlu menjadi perhatian untuk menghindari luapan informasi dari internet dan berusaha untuk tidak terlalu sering memeriksa ponsel pintar. Pemikiran serta perasaan tidak penting yang menumpuk dan tak terproses seperti sampah hanya akan menggangu kehidupan. Contohnya kebiasaan menunda keputusan, ketakutan, dan rasa bersalah. “Decluttering rumah hanya butuh waktu sekitar satu minggu. Tapi mental yang berantakan? Belajarlah mengatakan ‘tidak’, tetapkan batasan, beri perhatian untuk yang lebih baik. Itu akan bertahan selamanya,” ucap Sarah.
Tantangan yang kerap dihadapi para minimalis ialah berhadapan dengan komentar sinis orang lain. Benar, itu bisa atasi tapi tidak dihindari. Respons sebijak mungkin dengan meluruskan atau malah mengabaikan dan fokus terhadap diri sendiri. Hidup serumah dengan orang non minimalis cukup menjadi tantangan. “Untuk mengatasinya, saya memberikan saran pada keputusan orang tersebut dalam membeli. Kadang berhasil, kadang juga tidak,” ucap Chyntia.

Minimalisme, Konsumerisme, dan Kapitalisme
Konsumerisme dan kapitalisme adalah lawan paling berat di samping mengubah pola pikir. Dalam film dokumenter Minimalism: A Documentary About the Important Things karya Matt D'Avella, diperlihatkan bagaimana manusia menjadi senang mengonsumsi untuk mengisi kekosongan diri bukan kebutuhan. Konsumerisme membuat manusia mengejar benda untuk kepuasan belaka. Ekonom dan Sosiolog Juliet Schor, Ph.D. dalam film tersebut menyatakan kita terlalu materialistis dalam arti kata sehari-hari dan sama sekali tidak materialistis dalam arti sebenarnya. Kita perlu menjadi materialis sejati untuk benar-benar peduli dengan materialitas barang. Alih-alih, kita berada di dunia di mana material sangat penting makna simbolisnya. Kita berada dalam sistem berdasarkan pada apa yang dikatakan iklan atau marketing. Materialistis yang dimaksud adalah kepemilikan benda. Semestinya, saat memutuskan memiliki berarti kita benar-benar mengetahui nilai dan menghargai benda tersebut. Tetapi yang terjadi kini ialah perlombaan untuk memiliki sebanyak mungkin.
Tawaran minimalisme nampak cemerlang. Minimalisme bukan gerakan berhenti mengkonsumsi tapi cara untuk mengkonsumsi secara berbeda dan bertanggung jawab. Gagasan rupawan melawan konsumerisme dan kapitalisme ini bisa jadi berbalik. “Walaupun dapat dikatakan minimalisme sebuah tandingan untuk konsumerisme tapi bahaya komodifikasi gaya hidup ini tetap ada. Sehingga bukan tidak mungkin hanya menjadi tren sesaat,” ucap Daisy. Sebagian orang yang hanya mementingkan estetika dan ingin nampak bersahaja bisa mengisi rumah dengan benda berdesain minimalis berharga mahal. Lantas menyebut diri seorang minimalis. Padahal boleh jadi itu hanya persoalan selera. Seseorang tidak bisa dikatakan minimalis hanya dari memiliki benda berdesain minimalis. Kyle Chayka penulis buku The Longing for Less: Living with Minimalism juga merasakannya. Ia sering berpikir bahwa benda yang ia lihat bermerek minimalis itu mahal dan mewah. Baginya, minimalis seharusnya menjadi hal yang lebih merakyat. Ini bukan tentang harta Anda, ujarnya, tapi bagaimana Anda melihat dunia.

Ini memang hukum ekonomi yang sudah terjadi ribuan tahun lamanya. Ketika sesuatu menjadi tren dan permintaan pasar meningkat, maka produksi akan diperbanyak. Begitu juga persoalan ide minimalisme. Ia menjadi sebuah label bernilai jual dan punya kecenderungan dieksploitasi. Bukan tidak mungkin minimalisme malah menjadi kapitalisme itu sendiri. “Minimalis sebagai sebuah konsep telah sangat dikomodifikasi, seperti yang terlihat pada Marie Kondo yang menjual kristal dan garpu tala di situsnya. Minimalisme telah menjadi merek yang tidak memiliki banyak kesamaan dengan makna asli dari istilah tersebut,” kata Kyle Chayka, seperti dikutip dari Hazlitt.
Minimalisme tidak menghapus komsumerisme dan kapitalisme sepenuhnya sebab manusia tetap akan mengkonsumsi dan membeli. Meski begitu, masa depan minimalisme nampak cerah. Dilansir Forbes, minimalisme telah menginspirasi orang, terutama generasi milenial, untuk punya rumah kecil, isi lemari pakaian yang lebih sederhana, dan mendonasikan benda. Survey Harris Poll dan Eventbrite yang dikutip Bloomberg menyatakan 78 persen milenial suka menghabiskan uangnya untuk merasakan pengalaman daripada membeli barang. Membeli pengalaman dipercaya menimbulkan suasana hati positif yang tahan lama. Simplicity Institute merilis temuan dari total 2.500 orang di berbagai wilayan, 87 persen responden menunjukkan mereka lebih bahagia dalam keadaan cukup daripada ketika mereka memiliki lebih banyak harta.
Maka, menjadi minimalis adalah pilihan. Tergantung pada alasan dan tujuannya sendiri. “Menjadi minimalis tidak membuat kita merasa paling baik dan yang lain buruk. Semua kembali pada keputusan diri masing-masing. Kita tidak bisa memaksa. Orang yang memilih jadi minimalis punya perjalanannya sendiri. Mereka yang tidak karena memang tidak punya proses yang sama. Yang saya lakukan adalah berbagi info dan pengalaman, syukur jika tergerak melakukan hal serupa. Saya percaya kebiasaan baik pasti menular,” kata Chythia. Gaya hidup minimalis bukan hanya mengenai, kurang sama dengan lebih, kesederhanaan, kepemilikan benda, maupun pola pikir. Ia adalah gagasan menemukan esensi kebahagiaan hidup dengan sebaik-baiknya. (Wahyu Septiyani) Foto: Istimewa