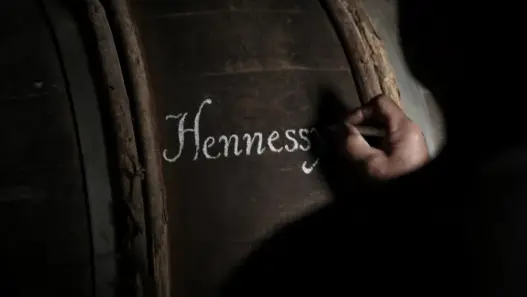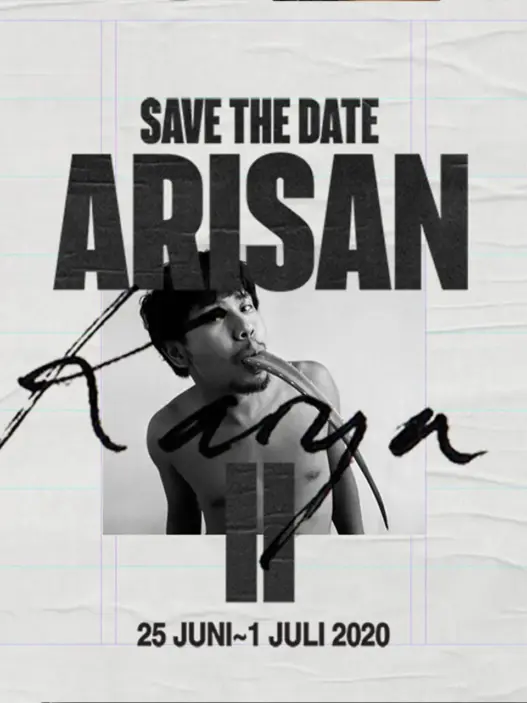Jika melihat tema-tema acara atau bahasa-bahasa pemasaran produk selama satu-dua tahun terakhir, ada satu istilah yang secara konstan akan Anda temui: “sustainable” atau “sustainability”. Atau “keberlangsungan” dalam bahasa Indonesia. Wacana tentang keberlangsungan itu kian memikat perhatian publik setelah pidato berapi-api Greta Thunberg: “Our house is on fire!” serunya, dan dunia ikut terbakar semangatnya.
Setelah itu seruan soal gaya hidup dan bisnis yang sustainable terus bergema, berulang, hingga tersaturasi maknanya sedemikian rupa hingga akhirnya identik dengan persoalan lingkungan. Padahal sebetulnya urusan sustainability adalah masalah hajat hidup. Ini lebih kepada masalah kita semua ketimbang masalah bumi. Dan karenanya jauh lebih kompleks dari sekadar persoalan mengenakan pakaian linen, menyetok tote bag, atau sedotan besi.
Mari kita preteli urusan sustainability ini. Let’s kil the jargon! Kita mulai dari yang paling mendasar. Apa itu sustainability alias keberlangsungan? Salah satu definisi yang diusung oleh organisasi-organisasi internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa dan World Bank ialah tentang memastikan “pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kebutuhan di masa yang akan datang”. Untuk itu, di dalamnya terdapat tiga elemen penting yang saling berkait, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Peneliti kebijakan publik dan ekonom lingkungan, Andhyta F. Utami menjelaskan model bisnis dikatakan sustainable menurut definisi-definisi organisasi internasional apabila ia bisa menghasilkan nilai ekonomi, dan di saat yang bersamaan juga membawa dampak positif bagi lingkungan dan sosial masyarakat. Atau dalam bahasanya sendiri, “Bagaimana manusia beraktivitas dengan cara yang memungkinkan manusia untuk terus bertahan hidup.”
Jadi jelas, urusan sustainability ini bukan tentang menyelamatkan bumi, tapi tentang menyelamatkan hidup dan peradaban kita hingga jauh ke masa yang akan datang. Kedengaran lebih egois memang, tapi begitulah adanya. Dan memang sudah kodratnya manusia sebagai makhluk yang egoistis. Egoisme adalah bagian yang inheren dari kehidupan di alam semesta, bahkan hingga ke level gen, Richard Dawkins telah menjelaskan argumennya secara rinci dan mendetail di buku The Selfish Gene. Ia menuliskan insting egois kita sebagai mesin kelestarian menyebabkan, “Acapkali tindakan yang tampak altruistik sesungguhnya adalah tindakan egois yang terselubung.” So, no shame.
Selanjutnya adalah apakah konsep bisnis yang berkesinambungan bisa diwujudkan dalam sistem ekonomi-politik kapitalistik seperti yang berjalan sekarang? Terutama dalam konteks mode. Industri mode, sebagaimana industri gaya hidup dan hiburan lainnya, seperti film, buku, musik, seni, dan sebagainya tumbuh dan berkembang dari ekses. Dalam hal ini ekses kapital. Bahkan dalam hal inovasi teknologi dan pengembangan ilmu pengetahuan sekalipun, ekses adalah sebuah keniscayaan.
Andhyta lebih lanjut menjelaskan, sejatinya bukan ide dasar kapitalisme tentang free market yang mendorong kompetisi dan memproduksi seefisien mungkin yang bermasalah. Melainkan market failure atau kegagalan pasar. Salah satu bentuk kegagalan pasar misalnya dari bagaimana sistem kapitalistik memberikan lebih banyak insentif-insentif jangka pendek. Hal ini terlihat nyata dari bagaimana keputusan-keputusan bisnis suatu perusahaan diambil berdasarkan hasil evaluasi kinerja keuangan dalam kerangka jangka waktu kuartal. Dampaknya, ada pengabaian akan implikasi jangka panjang yang krusial dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan. “Karena itu bukan kepentingan jangka pendek mereka,” katanya kepada Dewi.
Selain itu, masalah kedua dari sistem kapitalistik yang berlangsung saat ini adalah eksternalitas, atau “biaya” yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan harga produksi suatu barang. Andhyta mengambil contoh pembebasan lahan untuk hutan kelapa sawit dengan cara pembakaran.
“Membakar itu adalah opsi paling murah untuk membuka lahan. Tapi sebenarnya yang tidak dimasukkan ke biaya produksi yang dia keluarkan di akhir itu adalah semua dampak kesehatan, lingkungan, dan juga perubahan iklim,” kata Andhyta. Misalnya dampak kebakaran lahan gambut yang menurut estimasi World Bank, membuat Indonesia mengalami kerugian hingga US$ 16,1 miliar atau setara Rp 221 triliun pada 2015 dan US$ 5,2 miliar atau sekitar Rp 73 triliun pada 2019.
Kedua hal ini juga tercermin dari upah buruh murah. Termasuk di industri mode. Sudah rahasia umum bahwa praktik produksi barang mode kerap melibatkan sweatshop di negara-negara berkembang yang mempekerjakan orang dengan upah tak layak dan dalam kondisi kerja buruk. Upah buruh di industri mode yang terlampau murah ini merupakan bentuk kegagalan pasar, di mana banyak brand besar sekadar mementingkan efisiensi biaya dengan memilih negara atau pemasok termurah tanpa mengecek atau mengevaluasi praktik operasional mereka. Ini adalah bentuk eksternalitas karena dampak upah yang terlampau rendah tidak diperhitungkan oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Dampak-dampak itu antara lain, kualitas hidup pekerja yang rendah dan menyulitkan perkembangan mereka. Sehingga memperlebar kesenjangan.

Bias Kelas
Wacana soal “sustainability”, utamanya di industri mode, sama sekali bukan barang baru. Sudah sejak lama aktivis-aktivis di industri ini menyuarakan perkara kesinambungan operasionalnya. Ya, pada awalnya urusan “sustainability” di bidang fashion lebih berat membicarakan seputar kesejahteraan pekerja ketimbang persoalan lingkungan. Meskipun ketika itu, persoalan lingkungan juga sudah turut dibahas.
Ada beberapa asumsi mengapa kemudian isu tentang keberlangsungan industri menjadi seksi ketika ia dikaitkan dengan isu krisis lingkungan kini dan tidak ketika ia dikaitkan dengan isu kesejahteraan pekerja dulu. Pertama, ialah bahwa karena kini masalah lingkungan sudah sebegitu parahnya sehingga sulit untuk kita mengalihkan perhatian. Kedua, persoalan kesejahteraan pekerja, terutama buruh berupah rendah adalah hal yang dirasa jauh oleh kebanyakan kelas menengah.
Andhyta menjelaskan, bahkan ketika ia dikaitkan dengan wacana akan krisis lingkungan pun masih banyak kelas menengah yang menutup mata akan masalah lingkungan. Hasil survey YouGov-Globalism Project menunjukkan 18% orang Indonesia dari total 1.001 responden menyatakan tidak percaya bahwa perubahan iklim disebabkan oleh perbuatan manusia. Dalam survey itu memang tidak dijelaskan secara rinci dari kelas mana responden berasal. Akan tetapi dari diskusi di ruang publik, kita bisa melihat betapa masyarakat kelas bawah masih kerap disalahkan setiap kali terjadi bencana seperti banjir. Alasan mereka kurang teredukasi menjadi salah satu argumentasi.
Akan tetapi ada satu perspektif yang selalu luput, yaitu bahwa justru kelas menengah ataslah yang justru menyumbang emisi karbon terbesar. Inilah kelas yang setiap kali selalu membawa kendaraan pribadi ketimbang kendaraan publik. Kelas yang apartemen tempat mereka tinggal menyedot air tanah Jakarta hingga membuat banjir daerah di sekitar, tetapi dirinya sendiri terlindungi. Kelas yang setidaknya setahun sekali merencanakan liburan ke luar negeri. Hal-hal yang semuanya mempunyai dampak signifikan terhadap lingkungan.
Hal ini dijelaskan pula dalam laporan Vox dari hasil riset Stephanie Moser dan Silke Kleinhückelkotten berjudul “Good Intents, Low Impact”. Dalam riset tersebut Moser dan Kleinhückelkotten menemukan fakta bahwa para self-claim pencinta lingkungan yang berasal dari tingkat ekonomi-sosial tinggi cenderung menghasilkan emisi karbon yang lebih banyak, terhitung dari lahan yang mereka gunakan untuk tempat tinggal, energi yang digunakan, jumlah konsumsi daging, tingkat penggunaan mobil pribadi, hingga liburan. Sementara justru masyarakat kelas menengah bawahlah yang akan lebih merasakan dampaknya.
Ambil contoh kasus banjir di Jakarta awal tahun silam. Saat itu beredar foto aerial yang menampakkan sebuah komplek apartemen tetap aman dari banjir dengan kolam renangnya yang masih berwarna biru, sementara di luar tembok mereka banjir menggenang dengan air kecoklatan. Atau kasus pandemi yang kita alami sekarang ini. Pandemi COVID-19 pada dasarnya menyebar dengan cepat akibat perjalanan lintas-negara yang dilakukan oleh orang-orang dari kelas menengah dan menengah atas, tetapi dampaknya justru dirasakan paling parah oleh mereka yang berada di kelas menengah bawah. Tanpa menyadari ketimpangan ini, pada akhirnya kampanye sustainable lifestyle yang dilakukan, seperti namanya, hanya akan menjadi sebuah gaya hidup. Bukan mewujudkan sistem baru.
“Makanya, menurut saya perubahan itu mesti terjadi lebih sistematis,” ujar Andhyta. Artinya perubahan yang menyangkut ke mana para investor menaruh uang mereka dan bagaimana pemerintah membuat regulasi. “Karena konsumen itu cenderung autopilot. They just buy stuff.”
Peran pemerintah dalam mengintervensi pasar untuk mewujudkan sistem yang lebih langgeng memang krusial. Terutama dalam menjembatani ketimpangan di masyarakat. Meski belum ada penelitian lebih lanjut tentang ini, tetapi fakta menunjukkan ada korelasi antara peran pemerintah mewujudkan sistem yang berkesinambungan (sistem kesehatan mumpuni, redistribusi sumber-sumber daya, layanan publik dan jaring pengaman sosial, pembatasan polusi udara, dan kemampuan untuk mengoreksi kegagalan pasar) dan tingkat ketimpangan masyarakatnya. Ambil contoh negara-negara Skandinavia. Andhyta pun mengamini hal tersebut. “I don’t know if it’s a causation, but there is definitely correlation. Karena kalau pemerintahnya mulai memberlakukan pajak dengan lebih agresif, ada intervensi yang benar, dan retribusi untuk bikin sistem jaring pengaman sosial yang lebih baik, itu adalah indikator dari pemerintah yang fungsional. Dan berlaku kebalikannya,” jelasnya.
Pun ketegasan dari pemerintah seperti itu juga akan menjadi jaminan bagi para pelaku swasta untuk serius mengubah model bisnis mereka. Ambil contoh Uni Eropa yang sudah berkomitmen untuk beralih 100% ke energi terbarukan sebelum 2050. “Hal itu kemudian menjadi sinyalemen ke pasar untuk beralih ke energi terbarukan. Biarpun sekarang belum biayanya belum efisien, tapi paling tidak para pelakunya sudah mendapat jaminan jangka panjang atas investasi mereka,” jelas Andhyta.
Di Indonesia, pemerintah bukannya tidak punya perhatian ke isu ini. Lingkungan hidup sudah masuk ke dalam salah satu dari tujuh sektor dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Di situ tertera beberapa rencana pemerintah untuk menurunkan jumlah pembakaran hutan, menurunkan sampah, serta mengurangi polusi udara dan laut. Pemerintah juga sudah memasang target bauran energi 2025 hingga 30% untuk batu bara, 25% untuk minyak bumi, 23% untuk energi baru dan terbarukan (EBT), serta 22% untuk gas. Namun, memang pemerintah kita masih bergulat dengan komitmen eksekusinya yang inkonsisten. Tercermin dari banyaknya pembangkit listrik batu bara yang baru dibangun di zaman Joko Widodo. Pula subsidi baru bara dan adanya peraturan prosentase harga untuk sumber daya dari panel matahari.

Membangun Solidaritas Publik
Sebetulnya sikap pemerintah yang masih nampak setengah hati mewujudkan sistem yang berkesinambungan adalah karena isunya yang belum populis. Dan ini berkaitan erat dengan pembahasan wacananya yang amat bias kelas, membuat isu keberlangsungan hajat hidup ini seakan sesuatu yang ndaki-ndaki. Isu high brow. Padahal sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Salah satu sebabnya adalah penggunaan bahasa. Sering kali, para aktivis lingkungan hidup ini menggunakan bahasa yang terlalu text book dalam wacana besarnya, seperti istilah “sustainable” itu sendiri. Atau tujuan akhir zero net carbon emission. Atau zero waste. Akan tetapi kemudian lupa membumikan wacana abstrak tentang keberlangsungan hajat hidup tadi dengan, well, hajat hidup masyarakat kebanyakan untuk menjadikannya isu yang populis. Misalnya dengan menggaungkan persoalan banjir Jakarta yang semakin parah, sembari pelan-pelan memberikan edukasi akan keterkaitannya dengan krisis iklim. Begitu pula dengan isu kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan tempo hari. Kedua isu itu cukup berhasil menarik perhatian publik akan wacana krisis iklim dan keberlangsungan hajat hidup. Sebabnya, tak lain dan tak bukan karena masyarakat kebanyakan bisa langsung menangkap urgensi isu tersebut bagi kehidupan mereka. Bukan sekadar wacana abstrak nan utopis.
Menurut Andhyta, menerjemahkan wacana-wacana abstrak tentang keberlangsungan hajat hidup masyarakat kepada masyarakat menjadi amat penting untuk membangun solidaritas publik tadi. “Kalau mau benar-benar mengoreksi, mereka [para pegiat lingkungan] mestinya menghadapkan corongnya bukan ke pemerintah dulu, tapi ke rakyatnya dulu.” Alasannya sederhana, politisi punya insentif lima tahunan kepada pemilihnya di daerah konstituen mereka. Jadi strateginya adalah untuk menjadikan isu keberlangsungan hajat hidup ini sebagai isu yang cukup populis sehingga suka tak suka, harus dilirik para politisi.
Saya jadi teringat menemukan sebuah meme di linimasa media sosial saya. Meme itu menunjukkan gambar penjual jajanan pinggir jalan yang menjajakan Toppoki, camilan asal Korea Selatan yang oleh si penjaja dideskripsikan sebagai “Oseng Lontong Sayur Ala Korea.” Sekonyol apapun kelihatannya, senorak apapun terjemahannya, harus diakui si abang penjual makanan tadi berhasil membuka imajinasi dan memberi pemahaman kepada sebagian pembelinya yang mungkin masih awam, tentang apa itu Toppoki. Melihat itu, saya jadi terpikir semestinya para pegiat lingkungan hidup kita pun punya level artikulasi isu yang serupa si penjaja Toppoki. Itu tentunya jika kita memang serius hendak mewujudkan sistem baru yang berkesinambungan dan bukan sekadar ikut serta dalam tren wacana terkini. (Shuliya Ratanavara)