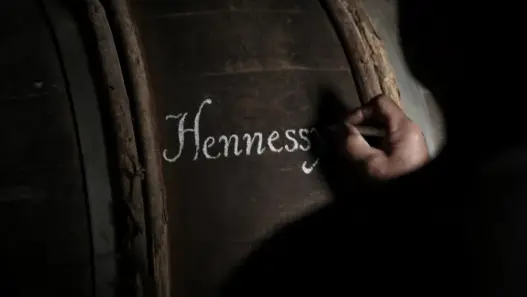Saya pikir, liputan ini akan berakhir sebagai pepesan kosong. Alias mbulet, membicarakan masalah tanpa perspektif baru. Pikiran ini didasari dari bagaimana term “sustainable fashion” adalah sebuah oksimoron. Ide akan fashion yang kita kenal hingga hari ini adalah ide tentang ekses. Contoh, kita memang butuh pakaian. Itu adalah satu dari tiga kebutuhan pokok kita sebagai manusia. Tapi kita tak butuh pakaian dengan aksen frill atau sentuhan ruffle yang mengaksentuasi siluet feminin perempuan modern seharga jutaan, apalagi hingga puluhan juta rupiah. You get the idea. Dan ya, kami pun menjadi salah satu bagian dari masalah ini.
Apalagi ide tentang “sustainability” kemudian digunakan sedemikian rupa hingga akhirnya kehilangan maknanya. Salah satu desainer yang telah lama vokal berseru tentang sustainable fashion, Stella McCartney pun mengakui kata yang satu itu kini sudah terlalu sering digunakan. “Tiba-tiba istilah itu ada di mana-mana dan orang-orang tak lagi benar-benar memahami apa maknanya,” katanya dalam salah satu seri webinar Vogue Global Conversation.
Persoalan kompleks tentang keberlangsungan hajat hidup masyarakat ini memang telah direduksi menjadi slogan pemasaran. Konsep besarnya lantas jadi tak lebih dari cantolan label yang membuat banyak dari kita merasa lebih baik karena telah “berkontribusi” untuk “menyelamatkan planet”. Pengamat kebijakan publik dan ekonom lingkungan, Andhyta F. Utami menjelaskan pada akhirnya kesadaran akan sustainability di kalangan kelas menengah baru sampai pada tahap afirmasi atau validasi status dan sosial. Itu mengapa kemudian fokus diskursus tentang konsep keberlangsungan hajat hidup di kalangan kelas menengah, khususnya di dunia mode, menyempit pada perihal lingkungan.
Padahal ada elemen-elemen lain yang juga perlu ditilik ketika kita benar-benar ingin mewujudkan dunia mode yang berjalan seiring sejalan dengan keberlangsungan hajat hidup orang banyak. Felicia Budi, desainer di balik brand fbudi misalnya menjelaskan baginya ada sustainable fashion tidak hanya mengurusi perihal ekologi, tetapi juga sisi sosial dan ekonomi. “Selain tiga poin itu, masih ada hal lain yang perlu dipikirkan, yaitu perihal kebudayaan dan hak kekayaan intelektual,” jelas Felicia kepada Dewi di butik sekaligus workshop-nya awal tahun ini.

Bagi Felicia, urusan sustainable fashion memang tidak hanya mencakup apa-apa yang terlihat, tetapi juga elemen-elemen yang tidak kasat mata. Sebabnya karena justru hal yang intangible ini yang nantinya akan mewujud dalam karya-karya mereka. Jangan sampai dalam merancang karya, seorang desainer mencuri kebudayaan atau kekayaan intelektual desainer lain. Pun jangan sampai tujuan besar mencapai mode yang terus berkesinambungan, justru membatasi ekspresi diri atau malah membuat mereka burn out. “Apa gunanya kita mencapai keseimbangan secara ekonomi, ekologi, dan sosial, tetapi desainernya burn out. Itu pada akhirnya tidak sustainable juga,” kata Felicia pasti.
Desainer di mata Felicia memang punya peran kunci dalam mewujudkan industri mode yang bisa terus berkesinambungan. “Kita juga harus mikirin, gimana pengolahan post-consumer.” Argumen Felicia didasarkan pada salah satu masalah terbesar dari industri mode adalah perihal limbah. Mulai dari limbah yang dihasilkan selama proses produksi, hingga limbah dari pakaian yang sudah tak lagi terpakai.

Hal yang sama diamini oleh Chitra Subiyakto, desainer penggagas brand Sejauh Mata Memandang. “Kami bekerja sama dengan Green Peace, Divers Clean Action, dan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Kita dapat data dari mereka bahwa pada 2019 di 49 titik perairan di Indonesia itu sampah tekstil jadi sampah yang terberat, sekitar 55% dari total sampah,” jelasnya. Hampir seluruhnya, sampah tekstil itu adalah polyester yang sulit terurai.
Industri mode memang telah lama memproduksi terlalu cepat dan terlalu banyak. Baik itu di tataran high fashion, dan apalagi di level fast fashion. Everyone’s guilty. Oleh karena itu kedua perancang busana ini mencoba mencari siasat yang bisa mereka lakukan lewat brand masing-masing. Kata kuncinya ialah circular fashion. Dengan kata lain betul-betul memikirkan produk dari awal hingga akhirnya. Tidak hanya memastikan proses produksinya dilakukan secara bertanggung jawab, tetapi juga bagaimana mengolah kembali produk yang dihasilkan setelah orang tak lagi memakainya.
Chitra menjelaskan misalnya bagaimana Sejauh Mata Memandang mempunyai program "Daur". “Bagaimana caranya kami menggunakan kembali pakaian yang sudah ada supaya terus terpakai. Jadi semua kain perca kita manfaatin lagi,” jelas Chitra ketika dihubungi Dewi via telepon. Kain-kain lama ini ia kumpulkan dari orang-orang yang bajunya sudah kekecilan, kebesaran, robek, atau sudah tidak terpakai lagi. Saat ini Sejauh Mata Memandang memulainya dengan hanya menerima pakaian warna putih untuk diolah kembali. Akan tetapi tujuan besarnya adalah untuk menampung dan mengolah kembali tekstil-tekstil yang tak lagi terpakai.
Sebagai sebuah brand pun, Sejauh Mata Memandang juga terus berusaha mempraktikkan praktik yang berkesinambungan secara holistik. Misalnya dengan menjalin kerja sama dengan pelaku usaha-usaha rumahan, bahkan hingga ke luar Jakarta. Rekanan Sejauh Mata Memandang misalnya ada di Pekalongan dan Solo. “Mereka bukan pabrik, mereka itu memang usaha rumahan yang dikelola keluarga turun-temurun. Tadinya bapaknya, terus ke anaknya,” kata Chitra.
Dinamika itu membuatnya seperti diingatkan lagi untuk menjadi manusia. Karena kemudian membuat proses yang terjadi di antara mereka tak sekadar transaksional. “Karena harus duduk sama-sama, ngobrol. Minum teh bareng. Cerita tentang anaknya sakit gigi, terus baru kita diskusi. Terus mereka juga memang orang yang peduli dengan usaha mereka. Jadi kita ngobrol sama pekerjanya pun senang,” paparnya.
Rekanan usaha lain yang juga mereka gandeng adalah ibu-ibu di Rumah Susun Marunda. Kerja sama itu bermula dari program mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dari program pemerintah, kerja sama ini lantas terjalin ke level yang amat personal baginya. Ia melihat sendiri perubahan besar yang dialami ibu-ibu ini. “Mereka awalnya bukan keluarga pembatik, tapi terus berlatih. Dari awal yang ngobrol ngeliat mata aja tidak berani. Sementara tiga bulan kemudian udah punya keterampilan itu udah lebih percaya diri. Mereka bilang seneng sudah bisa beli pulsa sendiri, atau sudah bisa nyicil motor, jadi enggak tergantung lagi dengan suaminya,” tutur Chitra penuh kesan.
Sementara Felicia memilih untuk bertransformasi mengganti model bisnisnya. Dari yang tadinya bergerak di sektor ready-to-wear, fbudi membelokkan kemudi ke jalur custom made. “Saya melihat masa depan fashion ada di bidang jasa ketimbang produk,” jelas Felicia. Ia melihat desainer punya peluang lain di luar jasa mendesain pakaian baru. “Sebagai seorang desainer kami bisa menawarkan jasa memperbaiki pakaian, memodifikasi pakaian, pun mendesain ulang pakaian yang tidak terpakai lagi,” ujar perempuan yang akrab dipanggil Feli ini.

Apa-apa saja yang ia jelaskan tentang sustainable fashion ia praktikkan dalam proses perubahan model bisnis ini. Peralihan untuk fokus membuat pakaian-pakaian secara custom tidak hanya didasarkan pada kesadaran untuk memproduksi lebih sedikit. Akan tetapi juga memperhitungkan peluang bisnis. Dari sisi produksi misalnya, Feli menjelaskan dirinya bisa menghasilkan produk dengan lebih efisien. Namun, tanpa mengorbankan sisi kreativitasnya. Di dalam model bisnis ini Felicia menemukan keseimbangan yang mungkin bisa menjadi satu peluang bagi fbudi.
Meski begitu, Feli menyadari betul model ini tidak mesti diadaptasi semua desainer. Setiap desainer, setiap brand pastilah mempunyai kekuatan dan tantangan yang berbeda. Dan perubahan serta solusi yang coba ditawarkan tiap desainer, agar menjadi sustainable tentunya mesti sejalan dengan DNA masing-masing.
Dalam kasusnya, Felicia melihat perkembangan pasar untuk produk mode sejenis dengan yang ia tawarkan. Sembari ia juga menimbang-nimbang ulang tujuannya sebagai seorang desainer. “Satu secara personal, setelah bertahun-tahun berkarya [membuat ready-to wear], saya merasa burn out. Capek. Terus saya bertanya ke diri saya apakah ini yang mau saya lakukan selama 20 tahun ke depan? Dan saya enggak melihat itu,” jelasnya.
Hal lain yang masih kerap luput dari percakapan tentang ekosistem industri mode yang berkesinambungan adalah tentang lokalitas. Bagaimana kita sebisa mungkin terlebih dulu mencari alternatif produk atau cara dari kearifan lokal. Felicia juga salah satu orang yang memang mengedepankan lokalitas. “Karena itu sudah pasti efeknya lebih baik ketimbang bergantung dari yang jauh. Misalnya dilihat dari jejak karbon kita,” jelas Feli. Meskipun ia juga tidak sama sekali menolak membeli barang dari luar negeri. Akan tetapi menurutnya kita perlu lebih banyak menimbang. Jangan sampai itu hanya menjadi pembelian impulsif.

Oleh karena itu, semestinya kita bisa lebih peka terhadap kearifan lokal Indonesia. “Kita bisa melihat lagi cara hidup kita dulu,” kata Chitra. Sejak dulu Indonesia udah eco-friendly banget. Nasi kita bungkus pakai daun, belanja kita pakai tas anyaman rotan. Modernisasi baratlah yang membuat kita kemudian beralih ke produk-produk serba cepat nan praktis. Ini pula yang dimaksud Felicia Budi ketika menjadikan kebudayaan sebagai salah satu variabel penting dalam membangun ekosistem industri mode yang berkesinambungan.
Kesadaran budaya juga kemudian bisa dapat menjadi alat bantu komunikasi publik tentang isu sustainability yang inklusif. Termasuk ke kelas masyarakat menengah ke bawah. Inklusivitas menurut Feli bukan dengan menyediakan alternatif produk yang lebih murah dalam jumlah yang lebih banyak untuk bisa diakses ke lebih banyak orang dari berbagai kelas sosial. “Saya tuh dulu pernah bilang sebenarnya bisa jadi perilaku konsumsi masyarakat menengah ke bawah itu lebih sustainable. Maksudnya, perputaran konsumsi mereka tidak akan secepat kelas menengah atas,” jelas Feli.
Tapi edukasi yang diberikan bukan untuk menyetel standar hidup baru. Akan tetapi menyegarkan kembali pengetahuan akan alternatif lain yang sempat ditinggalkan. “Saya terus terang merasa yang ditawarkan kepada masyarakat menengah ke bawah itu adalah jasa ketimbang produk baru. Entah itu untuk memperbaiki pakaian, atau belajar menyulam, dan sebagainya,” kata Feli yakin.
Sebab poin penting dari menjadi sustainable adalah bukan sekadar tentang memilih material baru yang lebih ramah lingkungan. Satu-satunya jaminan dari sekadar beralih jenis produk adalah bahwa ada setumpuk barang yang menjadi sampah karena tak lagi diinginkan orang. Lalu kemudian, menjadi masalah baru. Lebih dari itu, perlu juga dipikirkan cara-cara mengolah kembali material-material yang sudah ada di pasaran. Solusinya tidak sesederhana itu. Itu hanyalah salah satu dari begitu banyak hal yang mesti kita pikirkan bersama.
Poinnya adalah untuk melihat persoalan kesinambungan ekosistem industri dengan alam secara lebih holistik. Bukan hanya memilah mana bagian yang nyaman untuk dilakukan, seperti membeli pakaian baru dari bahan ramah lingkungan tapi kemudian hanya dikenakan sekali untuk satu gelaran acara. Sebagaimana hidup, kita perlu melihat produk apapun yang kita konsumsi sebagai satu bagian dari daur yang mesti diperhitungkan keberimbangan dan keberlangsungannya. Dari awal hingga akhirnya. (SHULIYA I RATANAVARA). Foto: Jonathan Raditya, Dok. Sejauh Mata Memandang.